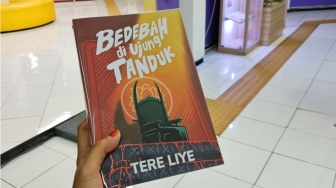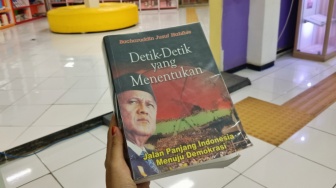Ibuku kehilangan anak tiga kali. Yang mati mungkin hanya satu, tetapi dua lainnya... tetap bernapas tanpa pernah benar-benar hidup.
Ibuku, bohong jika aku bilang tak sayang. Aku menyayanginya seperti anak-anak lain menyayangi ibu mereka. Dengan setia yang otomatis, dengan luka yang tak pernah benar-benar diberi nama. Ia bukan ibu yang jahat. Ia hanya manusia biasa, yang terlalu sering lupa bahwa cinta juga perlu adil.
Anak pertama ibuku perempuan. Kak Gina namanya. Kata orang, anak pertama adalah mahkota keluarga. Tapi sepertinya Kak Gina berada di situasi yang cukup rumit. Selain karena terlahir perempuan, ia juga harus mengalah karna ibu hamil lagi saat Kak Gina belum lepas asi.
Sejak itu, Kak Gina belajar satu hal paling awal dalam hidup. Mengalah tanpa diminta, diam tanpa dipuji.
Ia jarang dipeluk. Bukan karena ibu tak mampu, melainkan karena tangan ibu selalu sibuk menjaga kehidupan yang lain.
Aku sering melihatnya menangis pelan di kamar, menutup wajah dengan bantal seolah air mata pun tak pantas ditunjukkan. Ia tumbuh cepat. Bukan karena dewasa, melainkan karena tak diberi pilihan.
Anak kedua, namanya Irgi. Laki-laki. Ia datang seperti doa yang dijawab. Disambut senyum, disambut harap, disambut cinta yang berlebih.
Irgi adalah matahari keluarga. Kesayangan ibu dan ayah. Kesayangan kakek dan nenek. Segala salahnya mudah dimaafkan, segala tangisnya segera dipeluk.
Jika Kak Gina belajar mengalah, Irgi belajar dimenangkan. Aku menyaksikan itu setiap hari. Ketimpangan yang tak pernah diucapkan, tetapi terasa di udara rumah kami.
Aku, seperti yang sudah pasti. Anak ketiga. Hai namaku Lovana. Aku hanya suka mengamati. Apalagi, tentu saja tentang jomplangnya kasih sayang keluarga pada Irgi dan Kak Gina.
Kejadian naas itu belum terjadi. Hampir, akan aku ceritakan setelah ini.
Aku tumbuh di antara dua kutub. Seorang kakak yang dilupakan, dan seorang abang yang ditinggikan. Aku belajar membaca suasana, sebelum belajar membaca buku. Aku tahu kapan harus diam, kapan harus menyenangkan, kapan harus mengecil agar tidak merepotkan.
Saat itu kami masih keluarga yang tampak utuh jika dilihat dari luar. Baiklah mungkin ini sudah saatnya menceritakan tentang hari itu. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari lain di rumah kami.
Pagi masih muda ketika ibu sudah sibuk di dapur. Bau nasi hangat dan suara sendok beradu dengan panci memenuhi udara. Kak Gina duduk di ruang tengah, mengikat rambutnya sendiri dengan karet yang sudah longgar. Ia tak meminta bantuan. Ia sudah terbiasa.
Irgi berlari-lari kecil sambil menyeret mobil-mobilannya, sesekali menabrak kursi dan tertawa keras.
“Pelan, Gi,” kata ibu tanpa menoleh. Tapi nada suaranya lembut, bahkan nyaris seperti tertawa.
Aku duduk di lantai, memperhatikan semuanya. Seperti biasa.
“Bu, nanti pulang jam berapa?” tanya Kak Gina pelan.
Ibu berhenti sebentar, menoleh, lalu berkata singkat, “Nanti juga pulang. Kamu jaga adik-adik.”
Tak ada kata tolong. Tak ada terima kasih. Kak Gina hanya mengangguk. Hari naas itu datang diam-diam, seperti bayangan yang tak bersuara.
Menjelang siang, ibu harus pergi sebentar. Entah ke mana. Alasannya selalu sama: urusan sebentar. Irgi merengek ingin ikut.
“Jangan manja,” kata ibu, lalu memeluk Irgi singkat.
“Ibu cepat balik.”
Ia tidak memeluk Kak Gina. Tidak juga aku. Pintu ditutup. Suaranya keras, seperti palu yang diketukkan pada waktu.
Beberapa jam berlalu. Rumah menjadi terlalu sunyi. Irgi bosan. Ia mulai merengek, lalu menangis. Tangisnya pecah dan tak mau berhenti.
“Aku mau keluar,” katanya tiba-tiba.
“Mau nyari Ibu.”
“Kita nggak boleh keluar,” jawab Kak Gina cepat.
“Ibu bilang tunggu.” tambahnya lagi.
“Aku mau sekarang!” Irgi berteriak, kakinya menghentak lantai.
Aku ingat jelas raut wajah Kak Gina saat itu. Bukan marah, melainkan panik. Seperti seseorang yang tahu ia memegang sesuatu yang terlalu rapuh untuk dijaga sendirian.
“Gi, dengerin kakak…” Tangannya gemetar ketika menggenggam bahu Irgi.
Tapi Irgi meronta. Ia membuka pintu sendiri. Dan semuanya terjadi terlalu cepat untuk dimengerti anak-anak.
Suara rem mendecit. Teriakan orang.
Tangis yang bukan lagi tangis anak kecil.
Aku ingat Kak Gina berteriak memanggil nama Irgi berkali-kali. Suaranya pecah, tubuhnya berlari tanpa arah. Aku hanya berdiri, kaki terasa menancap di lantai, tak bisa bergerak.
Orang-orang mengerumuni sesuatu di jalan. Ketika ibu datang—aku masih ingat—langkahnya terhenti di tengah jalan. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang tas.
“Ada apa?” tanyanya. Tak ada yang langsung menjawab.
Seseorang berkata pelan, “Bu… anaknya…”
Ibu berlari. Lalu jatuh berlutut. Tangisnya bukan tangis manusia yang kehilangan, melainkan jerit sesuatu yang hancur di dalam.
Irgi pergi hari itu.
Ia tidak pulang. Tidak tumbuh besar. Tidak sempat menjadi apa-apa.
Kak Gina benar-benar tak lagi terlihat. Ia ada di rumah, tetapi tak pernah dipanggil namanya dengan penuh cinta. Dan aku? Aku kehilangan ibu dalam diam.
Ibuku berkabung sepanjang hidupnya, tetapi tak pernah belajar mendengar. Ia mencintai dengan luka, dan melukai dengan cinta.
Kini aku mengerti. Kehilangan tidak selalu tentang kematian. Kadang ia tentang tak pernah benar-benar dipeluk meski masih duduk di meja yang sama.
Dan sejak hari itu pula, ibuku menjadi sosok yang kehilangan semua anaknya. Ibu kehilangan anak lelakinya karena kematian, dan kehilangan dua anak lainnya karena pengabaian.
Kak Gina hidup, tapi jiwanya tertinggal di jalan itu. Ia tak pernah lagi tertawa dengan suara penuh. Tak pernah lagi meminta apa pun. Ia tumbuh dengan rasa bersalah yang tak pernah menjadi miliknya.
Aku hidup, tapi belajar sejak dini bahwa cinta bisa timpang, dan kehilangan tidak selalu berwujud makam.
Ibuku kehilangan anak tiga kali.
Satu di jalan itu.
Dua lainnya…
perlahan,
di dalam rumah yang sama.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS