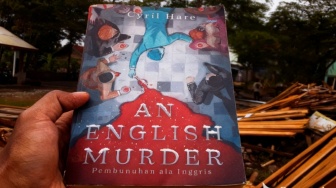Perkenalkan, namaku Natalia. Sebentar lagi bayi mungil di dalam perutku akan keluar. Bukaan terakhir terasa seperti hukuman. Nyeri yang tak lagi bisa ditawar.
Rintihan demi rintihan lahir bersama napasku yang putus-putus. Aku menjalaninya seorang diri. Tanpa keluarga. Tanpa tangan yang menggenggam. Sungguh, kesepian terasa lebih menyakitkan daripada kontraksi itu sendiri.
Gelisahku sedikit mereda ketika sekelompok dokter ahli berusaha menenangkan batinku. Pemimpin mereka menganjurkan alternatif persalinan, prosedur yang diprioritaskan untuk kasus kehamilanku.
Aku menolak. Tak peduli seberapa besar risikonya. Aku memilih melahirkan secara normal. Aku siap menghadapi apa pun termasuk mati.
Jika boleh menebak isi hati perempuan-perempuan yang sedang berada di ambang persalinan, mungkin inilah momen paling krusial dalam hidup mereka. Setidaknya, itulah yang kurasakan.
Demi titipan Sang Maha Esa, tubuh dipaksa bertarung melawan rasa sakit yang menjelma nyeri bercampur pedih. Rasanya seperti silet menyayat dari perut hingga selangkangan.
Untunglah, semua itu berlalu. Bayi mungilku berhasil keluar. Namun ketenanganku tak pernah benar-benar utuh. Setelah melahirkan, empat puluh delapan jam aku terbaring di ruang khusus pasien, dan tak sekalipun aku diizinkan melihat, apalagi menimang bayiku sendiri.
Kesabaranku terkikis. Aku memaksa salah satu kru medis menjelaskan alasan di balik peraturan rumah sakit yang terasa janggal. Pikiranku melenceng, curiga, menuduh tanpa dasar. Aku meyakini ada sesuatu yang disembunyikan.
Tak lama kemudian, ada suster masuk ke ruanganku. Dengan suara datar, dia menyebutkan lokasi ruangan bayiku dan mengimbau agar aku tetap tenang sambil mengikutinya.
Kami pun berjalan menyusuri lorong-lorong sunyi. Hingga tiba di sebuah ruangan serba putih, dingin, dipenuhi kotak-kotak inkubator. Beberapa dokter tampak berdiskusi sambil mengerubungi salah satunya.
Dadaku mendadak terasa diremas sesuatu yang tak kasatmata. Jantungku berdegup tak beraturan. Ada firasat buruk yang tumbuh, tapi kupaksa menyingkirkannya. Waktu akan terbuang sia-sia jika aku terus memikirkan yang tidak-tidak.
Kami pun memasuk ruang inkubasi. Tak lama, ada dokter lelaki menyentuh bahuku, tersenyum terlalu lebar. Dia mengatakan sesuatu, aku mengangguk, meski tak benar-benar memahami ucapannya.
Lalu, akhirnya, aku dipersilakan menatap anakku. Aku tersentak.
Pada detik yang sama ketika aku tersentak, masa lalu menyala di kepalaku seperti kilat. Aku melihat diriku sendiri yang menikmati hidup dengan melacurkan tubuh.
Bukan hanya menjual raga, tapi juga memberikan kepuasan birahi pada setiap pria yang pernah mengikat janji denganku. Hingga suatu hari aku hamil, tanpa tahu siapa yang paling layak disebut ayah.
Ibu dan bapak syok saat mengetahui kenyataan itu. Bapak mengusirku sambil melontarkan sumpah berisi makian. Tak lama setelah kepergianku, ibu meninggal.
Dan kini, di hadapanku, sesuatu itu terbaring tanpa bisa kusebut apa. Kaca inkubator memantulkan wajahku yang pucat. Di baliknya, ada gerak kecil—bukan napas, bukan tangis. Hanya denyut pelan yang teratur.
Kulitnya pucat dan licin, menegang di atas daging yang memanjang lurus. Tak ada lekuk bahu. Tak ada sendi. Ujungnya tumpul, dingin, berhenti begitu saja.
Aku mencari bentuk tangan. Tak kutemukan. Aku mencari bentuk kaki. Tak pernah ada. Dan ketika aku memperhatikan lebih jeli wajah bayiku, yang kulihat hanyalah permukaan kosong. Aku pun limbung.
Sumpah ayahku menggema kembali di telingaku:
“Anak tidak jelas itu ibarat pohon tanpa ranting dan daun. Cuma batang. Batang hidup yang tak akan pernah tumbuh. Enyahlah kau!”
Purbalingga, 30 Des 2025