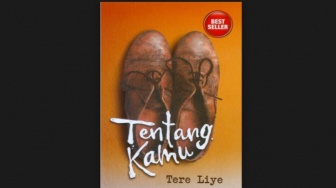Senja di kota itu selalu datang dengan warna yang lembut. Jingga yang perlahan berubah merah muda, lalu ungu tipis sebelum benar-benar tenggelam dalam gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu per satu, dan suara penjual takjil di pinggir jalan saling bersahutan.
“Kolak pisang hangat!”
“Es buah segar!”
“Gorengan baru angkat!”
Alya berdiri di depan pagar rumahnya, memandang jalan kecil yang mulai ramai oleh orang-orang yang menunggu waktu berbuka. Udara sore membawa aroma minyak panas dan gula merah yang dimasak lama. Perutnya sedikit berbunyi.
Ia baru saja pulang dari kampus. Tas selempangnya masih menggantung di bahu, rambutnya yang sebahu diikat seadanya. Rumahnya berdiri di ujung gang sempit, cat temboknya mulai mengelupas di beberapa bagian. Ia tinggal berdua dengan ibunya sejak kecil. Ayahnya menghilang lima belas tahun lalu. Tanpa kabar maupun penjelasan.
“Alya, azan lima menit lagi!” suara ibunya terdengar dari dalam rumah.
“Iya, Bu!” sahut Alya.
Saat itulah sebuah motor berhenti tepat di depan pagar. Alya menoleh. Pengendara itu mengenakan jaket hitam dan helm full face gelap. Tanpa membuka helm, ia turun sebentar, meletakkan satu kantong plastik putih di atas pagar, lalu kembali naik dan melaju pergi. Alya membeku beberapa detik.
“Eh!” serunya, tapi motor itu sudah berbelok di tikungan. Ia mendekat perlahan. Di dalam kantong plastik itu ada kotak mika berisi kolak, sebungkus gorengan, dan sebotol air mineral kecil. Tanpa catatan seperti orang yang bagi takjil pada umumnya.
Alya mengernyit. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada tetangga yang sedang bercanda. “Siapa, Alya?” ibunya keluar, menyeka tangan dengan lap dapur.
“Ada yang ngirim takjil, Bu. Tapi nggak tahu dari siapa.”
Ibunya mendekat, memeriksa isi kantong. “Mungkin dari teman kampus kamu?”
Alya mengangkat bahu. “Nggak ada yang bilang mau kirim.”
Azan Magrib berkumandang dari masjid di ujung gang. Suaranya bergema lembut di antara rumah-rumah. Ibunya tersenyum kecil. “Sudah, kita buka saja. Anggap rezeki.”
Alya ragu sejenak, tapi aroma gorengan yang hangat membuat perutnya semakin memberontak. Mereka masuk ke dalam. Malam itu, takjil terasa biasa saja. Manis. Hangat. Tidak ada yang aneh. Hanya saja, sebelum membuang kertas pembungkus gorengan, Alya sempat memperhatikan sesuatu. Kertasnya bukan kertas minyak biasa, melainkan potongan koran lama. Huruf-hurufnya agak pudar. Ia tidak terlalu peduli. Ia membuangnya ke tempat sampah.
Hari berikutnya, hal yang sama terjadi. Menjelang Magrib, motor berjaket hitam itu muncul lagi. Kantong plastik diletakkan, lalu pengendara itu pergi tanpa sepatah kata. Kali ini Alya sempat berlari ke pagar.
“Tunggu!” teriaknya. Namun suara knalpot motor menenggelamkan suaranya. Ia kembali memeriksa isi kantong. Kolak. Gorengan. Air mineral.
Ibunya tersenyum heran. “Mungkin ada yang ingin bersedekah.”
Alya menggigit bibir bawahnya. “Tapi siapa?”
Saat membuka bungkus gorengan, ia kembali melihat potongan koran. Entah kenapa, kali ini matanya tertahan lebih lama.
“… dilaporkan hilang sejak tiga hari lalu …”
“… keluarga korban belum mendapat kepastian …”
Alya berhenti membaca. Ada foto kecil di pojok potongan itu. Buram, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Wajah itu terasa sangat familiar di ingatan Alya. Wajah yang pernah ia lihat berkali-kali dalam album lama ibunya. Ia berdiri terpaku.
“Bu …,” suaranya pelan.
Ibunya menoleh. “Kenapa?”
Alya membawa kertas itu mendekat ke lampu. “Ini… mirip Ayah.”
Ibunya terdiam. Wajahnya berubah perlahan, seperti bayangan yang menutupi cahaya. “Mana?” tanyanya pelan.
Alya menyerahkan potongan koran itu. Ruangan kecil mereka terasa mendadak sempit. Suara azan yang biasanya menenangkan kini terasa jauh. Ibunya duduk pelan di kursi kayu. Tangannya gemetar saat menyentuh foto buram itu.
“Itu … berita lama,” bisiknya.
“Bu, ini bukan kebetulan, kan?”
Ibunya tidak menjawab, malah mengajak Alya makan takjil tersebut.
Malam itu Alya tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, membuka kembali tempat sampah, mengambil potongan koran yang sempat ia buang hari sebelumnya. Ia menyusunnya di atas meja belajar. Beberapa potongan ternyata saling berkaitan.
“… kasus orang hilang di Kawasan …”
“… diduga terkait konflik bisnis keluarga …”
“… nama yang disebutkan adalah …”
Bagian itu terpotong. Alya merasakan dingin merambat di punggungnya. Ia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Senyum pria itu hangat, berbeda dengan kesan misterius dalam potongan berita tadi.
“Kenapa baru sekarang?” gumamnya.
Di luar, suara motor melintas pelan. Alya tersentak dan mematikan lampu kamar. Ia mendekat ke jendela, mengintip melalui celah tirai. Motor hitam itu berhenti di ujung gang. Lampunya mati. Pengendara itu duduk diam beberapa detik sebelum akhirnya pergi. Alya menelan ludah.
***
Hari ketiga, ia menunggu di balik pagar sebelum waktu Magrib. Motor itu datang lagi. Begitu pengendara turun, Alya langsung membuka pagar. “Siapa kamu?” tanyanya tegas.
Pengendara itu berhenti sebentar. Helmnya masih menutupi wajah. Ia tidak menjawab. Hanya meletakkan kantong plastik seperti biasa.
“Kenapa kirim ini? Apa maksudnya?” suara Alya bergetar.
Sunyi beberapa detik. Lalu, pelan, pengendara itu berkata, suaranya teredam helm, “Baca semuanya.”
Alya membeku. Motor itu langsung melaju pergi. Ia berdiri mematung beberapa saat sebelum kembali masuk. Tangannya gemetar saat membuka bungkus gorengan. Potongan koran kali ini lebih besar.
“… penyelidikan dihentikan karena kurang bukti …”
“… dugaan keterlibatan pihak internal keluarga …”
Alya merasakan napasnya memendek. Internal keluarga? Ia menoleh ke arah dapur. Ibunya sedang menuang teh dengan wajah pucat.
“Bu,” suara Alya nyaris berbisik, “apa yang sebenarnya terjadi dulu?” Ibunya tidak menoleh.
“Tidak semua hal perlu dibuka lagi, Alya. Biarkan semuanya berlalu, Ayahmu sudah tenang di sana.”
“Tapi, Bu. Seseorang sedang mengirim ini pada kita. Koran ini menunjukkan kalua penyeledikan waktu itu belum selesai.”
Ibunya memejamkan mata. Hening menggantung di antara mereka. Lagi-lagi, Alya tak memperoleh jawaban yang dia harapkan dari ibunya.
Beberapa hari berikutnya, potongan koran semakin lengkap. Alya mulai menyusunnya seperti puzzle di kamar. Di antara potongan-potongan itu, muncul satu nama yang membuatnya terdiam lama. Nama pamannya. Adik ayahnya. Yang sejak dulu jarang datang dan selalu menghindari pembicaraan soal masa lalu.
“…perselisihan terkait pembagian aset…”
“…korban terakhir terlihat bertemu dengan saudaranya…”
Alya duduk bersandar di dinding. Tangannya terasa dingin. Di luar, suara takbir tarawih terdengar dari masjid. Kontras dengan ketegangan yang mengikat dadanya. Malam itu, sebelum tidur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tak dikenal.
Besok malam. Ikuti motorku.
Alya menatap layar itu lama. Ia tahu ia seharusnya takut. Tapi rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya.
Malam berikutnya, motor itu datang lebih lambat dari biasanya. Alya sudah berdiri di depan pagar. Pengendara itu memberi isyarat agar ia mengikuti. Alya ragu sejenak, lalu mengambil jaket dan memberi tahu ibunya, “Aku ke depan sebentar.”
Ia mengikuti motor itu dengan sepeda kecilnya, menjaga jarak. Gang sempit berubah menjadi jalan raya, lalu masuk ke kawasan yang lebih sepi. Lampu jalan jarang. Suara jangkrik mendominasi. Motor itu berhenti di depan bangunan tua yang tampak tak terurus. Pabrik lama dengan pintu besinya yang sudah berkarat.
Pengendara motor itu akhirnya turun dan membuka helm yang menyamarkan identitasnya selama ini. Alya menahan napas saat mengetahui laki-laki itu ternyata bukan orang asing, tetapi sepupunya sendiri. Rafi.
“Kamu?” bisik Alya.
Rafi menatapnya dengan wajah serius. “Aku nggak mau kamu terus dibohongi.”
“Apa maksudnya semua ini?”
Rafi mengeluarkan map cokelat dari tasnya. “Ini berkas kasus Om yang nggak pernah selesai dulu. Saat itu memang ada yang sengaja menutupinya.”
“Siapa?”
Rafi menatapnya dalam. “Ayahku terlibat. Motifnya warisan.”
Alya tersentak. Takut-takut, ia melangkah mundur. Kenyataan itu membuatnya terdiam beberapa saat. Selam aini, dia hanya mengenal sosok ayah dari cerita ibunya. Terkhir kali bertemu, mungkin saat ia masih berusia sekitar lima tahun. Ingatannya tentang sosok ayah bahkan sudah nyaris pudar.
“Kalian berhasil menutupinya dengan baik. Kenapa malah dibuka lagi sekarang?”
“Ayahku sakit keras. Umurnya mungkin hanya tersisa beberapa hari lagi. Aku kemari untuk menyampaikan maaf dari beliau. Maaf, Alya. Tolong, maafkan keserakahan ayahku yang membuatmu tumbuh tanpa ayah.”
Sunyi mengisi ruang kosong di antara mereka. Alya bingung harus merespon seperti apa. Dia memang marah pada orang yang membunuh ayahnya, tapi semua itu sudah berlalu. Ibunya sudah lama memilih Ikhlas. Alya memandang pabrik tua itu.
“Kenapa di sini?” tanyanya.
“Ayahmu ditemukan di sini waktu itu.”
Lampu senter menyala, menerangi lantai berdebu dan mesin-mesin tua. Alya melangkah masuk mengikuti Rafi. Semakin ke dalam, napas Alya terasa semakin sesak. Kalimat terakhir yang diucapkan Rafi terus terngiang di kepalanya. Adegan demi adegan terbayang tanpa permisi membuat matanya berkaca-kaca.
Di balik mesin besar, Rafi menunjukkan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi. Di dalamnya ada sebuah jam tangan. Alya menutup mulutnya, menahan isak. Kedua tangannya bergetar menerima kotak tersebut. Samar-samar, ingatan tentang ayahnya berputar bagaikan film. Jam tangan itu … benar-benar jam yang selalu dipakai ayahnya ke mana-mana. Alya terdiam begitu lama menatap benda kecil itu yang terasa lebih berat dari dunia. Isakan demi isakan kecil lolos dari bibirnya. Sementara Rafi hanya diam. Membiarkan Alya larut dalam kenangan bersama sang ayah yang sudah lama dia rindukan.
***
Beberapa minggu setelah Ramadan, laporan lama dibuka kembali. Bukti baru muncul. Nama-nama disebut. Rahasia keluarga yang terkubur bertahun-tahun mulai terkuak. Namun, apa gunanya semua itu? Terduga pelaku, ayahnya Rafi meninggal dunia akhir bulan Ramadan kemarin. Penyelidikan ulang hanya terasa seperti formalitas, pelaku tak dapat dihukum.
Di beranda rumah, Alya duduk bersama ibunya. Langit sore berwarna jingga. Udara terasa hangat. Ibunya menggenggam tangannya erat.
“Maafkan Ibu,” bisiknya.
Alya menyandarkan kepala di bahu ibunya. Ramadan telah usai. Takjil gratis itu tak lagi datang. Tapi pesan-pesan di balik bungkusnya telah membuka sesuatu yang selama ini terkubur dalam diam. Dan di antara suara adzan Magrib yang kembali berkumandang, Alya menyadari bahwa kebenaran memang tidak selalu datang dengan cara yang nyaman. Kadang ia dibungkus seperti gorengan hangat yang terlihat sederhana di luar, tapi menyimpan sesuatu yang mengubah hidup seseorang di dalamnya.