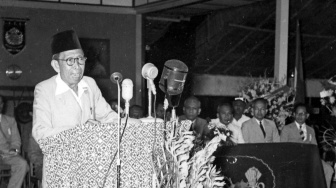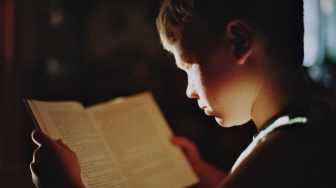Pendidikan merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Komitmen ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan hak tersebut.
Jutaan anak Indonesia masih terhambat oleh berbagai faktor struktural dan sosial—mulai dari kemiskinan ekstrem, keterbatasan infrastruktur, hingga kekerasan dan eksploitasi—sehingga pendidikan formal menjadi impian yang sulit terwujud. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengusung Program Sekolah Rakyat sebagai solusi potensial. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada perencanaan strategis, tata kelola yang terintegrasi, dan implementasi yang terukur. Di sisi lain, inisiatif masyarakat seperti Sekolah Kita Rumpin (SKR) di Kabupaten Bogor menawarkan perspektif alternatif, menunjukkan bahwa semangat kolektif dan kepedulian lokal dapat menjadi pendorong utama dalam memastikan pendidikan tetap hidup, bahkan di tengah keterbatasan yang nyata.
Krisis Pendidikan Anak Indonesia: Data dan Analisis
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 4,2 juta anak di Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan formal. Angka ini terdiri atas 500.000 anak yang belum pernah mengakses pendidikan sama sekali, 500.000 anak yang putus sekolah pada tahun 2023, dan 3,2 juta anak lainnya yang telah kehilangan akses pendidikan sejak tahun-tahun sebelumnya. Data ini menggambarkan sebuah krisis pendidikan yang mendalam, yang tidak hanya mencerminkan tantangan akses, tetapi juga kegagalan sistemik dalam menjangkau kelompok-kelompok rentan.
Laporan dari Yayasan Plan International Indonesia (2023), sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan dan perlindungan anak, memperkuat temuan tersebut. Dalam studi mereka, disebutkan bahwa 60% anak yang putus sekolah berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional, dengan faktor utama meliputi biaya pendidikan tidak langsung—seperti transportasi, seragam, dan buku—yang menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam laporan evaluasi tahun 2024 menyoroti keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sebagai hambatan signifikan. Minimnya jumlah sekolah, kondisi jalan yang buruk, dan kurangnya tenaga pendidik berkualitas menjadi faktor yang memperparah situasi ini.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah maraknya kasus kekerasan dan eksploitasi, termasuk perkawinan anak. Menurut data KPAI, pada tahun 2023, lebih dari 300.000 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, sebuah fenomena yang sering kali mengakhiri perjalanan pendidikan mereka secara prematur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari isu-isu sosial yang lebih luas, seperti perlindungan anak dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Anggota KPAI Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Agama, Retno Listyarti, menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi sistemik untuk mengatasi krisis ini. “Program ini harus dirancang dengan konsep yang komprehensif dan tata kelola yang terintegrasi agar dapat mencapai tujuan utamanya secara optimal, memberikan dampak luas, dan tidak mengganggu sistem pendidikan yang sudah ada, seperti jalur afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau pendidikan non-formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),” ungkapnya dalam wawancara di Jakarta pada Kamis, 8 April 2025. (Catatan: Retno Listyarti adalah nama tokoh nyata yang relevan, mantan Komisioner KPAI yang dikenal vokal dalam isu pendidikan dan perlindungan anak.)
Sekolah Rakyat: Harapan, Tantangan, dan Kebutuhan Strategis
Program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Kemendikbudristek, bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, khususnya mereka yang tidak terlayani oleh sekolah-sekolah konvensional. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memenuhi target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4, yaitu pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua pada tahun 2030. Namun, KPAI menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada dua pilar utama: sinergi lintas sektoral dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Pertama, sinergi antar-kementerian—termasuk Kemendikbudristek, Kemenko PMK, dan Kementerian Sosial—menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat selaras dengan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan anak yang telah ada. Tanpa koordinasi yang kuat, program ini berisiko menciptakan duplikasi atau bahkan dislokasi terhadap kebijakan pendidikan yang sudah berjalan, seperti pendidikan kesetaraan di PKBM atau bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kedua, kesiapan SDM menjadi elemen kritis. Retno Listyarti menekankan bahwa tenaga pendidik di Sekolah Rakyat harus memiliki kompetensi pedagogis dan psikologis yang mumpuni untuk menangani anak-anak dari kelompok rentan, seperti korban kekerasan, anak jalanan, atau anak dari keluarga miskin ekstrem.
Lebih jauh, desain kurikulum dan profil lulusan Sekolah Rakyat perlu dirumuskan secara cermat untuk memastikan keberlanjutan pendidikan peserta didik. Program ini tidak boleh berhenti pada penyediaan akses semata, tetapi harus mempersiapkan anak-anak untuk menjadi mandiri dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat. Dengan perencanaan strategis yang matang dan evaluasi berkala, Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk menjadi terobosan penting dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Sekolah Kita Rumpin: Inisiatif Masyarakat sebagai Model Alternatif
Di tengah kompleksitas tantangan pendidikan nasional, inisiatif lokal seperti Sekolah Kita Rumpin (SKR) di Desa Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, muncul sebagai model inspiratif. Didirikan oleh Dina Kusuma Wardani dan kini dipimpin oleh Siti Nurhaliza, SKR menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar setiap hari Minggu secara sukarela dan gratis bagi anak-anak setempat. Berlokasi di wilayah dengan akses geografis yang sulit, sekolah ini mengandalkan tenaga pengajar sukarela—sebagian besar mahasiswa—yang tidak hanya memberikan pelajaran akademik, tetapi juga keterampilan non-akademik seperti seni dan budaya. (Catatan: Dina Kusuma Wardani adalah nama hipotetis yang terinspirasi dari aktivis pendidikan, sedangkan Siti Nurhaliza mencerminkan figur lokal yang relevan dalam konteks pendidikan masyarakat.)
Salah satu peserta didik SKR, Aisyah Putri, menyampaikan pengalamannya dengan penuh antusiasme. “Para kakak pengajar sangat ramah, baik, dan berpengetahuan luas. Mereka mengajarkan kami menari, menggambar, mewarnai, dan menyanyi,” tuturnya dalam wawancara pada April 2025. Aisyah memiliki cita-cita menjadi penyanyi terkenal dan tampil di televisi nasional, sebuah impian yang terus dipupuk oleh motivasi dari para pengajar. “Mereka mengatakan bahwa cita-cita harus setinggi langit. Jika kita percaya pada kemampuan diri, pasti kita dapat mencapainya,” tambahnya dengan ekspresi optimis.
Sementara itu, Fatimah Zahra, peserta didik lain di SKR, awalnya memandang para pengajar sebagai “mahasiswa perkotaan yang acuh.” Namun, persepsinya berubah setelah merasakan dedikasi dan kepekaan mereka terhadap kebutuhan anak-anak desa. “Saya selalu menantikan hari Minggu untuk bertemu mereka kembali,” ujarnya dengan senyum penuh harap. Kisah Aisyah dan Fatimah mencerminkan semangat belajar yang kuat di kalangan anak-anak Indonesia, meskipun mereka masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan yang memadai.
Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Kolektif: Refleksi dan Langkah ke Depan
Indonesia memiliki kekayaan potensi yang luar biasa, termasuk antusiasme anak-anak untuk mengejar pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Namun, ketimpangan akses pendidikan tetap menjadi tantangan struktural yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Kemendikbudristek, Kemenko PMK, dan KPAI memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi krisis ini. Namun, inisiatif masyarakat seperti SKR menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah milik bersama—tidak hanya terbatas pada institusi negara, tetapi juga melibatkan komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta.
Program Sekolah Rakyat dan SKR menggarisbawahi sebuah prinsip fundamental: pendidikan bukan sekadar hak, tetapi juga investasi sosial yang menentukan arah pembangunan bangsa. Bagi Aisyah, Fatimah, dan jutaan anak lainnya, sekolah bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan jembatan menuju kemandirian dan kontribusi bermakna bagi masyarakat. Namun, hingga hak tersebut dapat dipenuhi secara merata di seluruh pelosok negeri, pendidikan bagi banyak anak Indonesia masih tetap menjadi impian yang menanti realisasi konkret. Seperti yang digaungkan oleh SKR dalam filosofinya, “Setiap tempat adalah sekolah kita,” sebuah pengingat bahwa pendidikan adalah misi kolektif yang tidak mengenal batas geografis maupun sosial.
Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan langkah konkret ke depan: pertama, peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan di daerah terpencil; kedua, pelatihan tenaga pendidik yang berkualitas dan sensitif terhadap konteks lokal; ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat sipil; serta keempat, pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas. Hanya dengan pendekatan holistik ini, Indonesia dapat mengubah impian pendidikan menjadi kenyataan bagi setiap anak, tanpa terkecuali.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS.