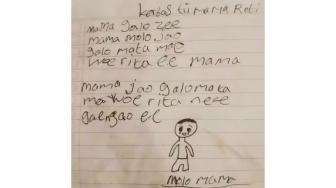Di sebuah pendopo sederhana di Yogyakarta, alunan suling bambu terdengar lembut. Jemari Pak Agus menari di atas lubang-lubang kecil, meniupkan melodi yang seakan membawa siapapun yang mendengarnya pada ketenangan batin. Dari wajahnya, terlihat ketulusan seorang seniman yang tak sekadar memainkan alat musik, tetapi juga menjaga napas panjang sebuah tradisi.
Agus Budi Nugroho, atau akrab disapa Agus ‘Patub’ BN, lahir di Kebumen 49 tahun lalu, dari keluarga dokter dan bidan. Ia anak bungsu dari lima bersaudara, tapi sejak kecil memilih jalur berbeda: musik.
Di usia sepuluh tahun ia belajar otodidak, ikut band sekolah, karawitan, kasidah, bahkan grup rock kampung. Eksperimen bunyi baginya adalah cara mengekspresikan diri; ia pernah menciptakan komposisi dari suara orang makan kerupuk.
Sejak menetap di Yogyakarta pada 1994, Agus menjadikan kota ini sebagai panggung kreativitasnya. Ia menulis lagu, menciptakan jingle, mengisi musik teater, hingga menggarap pertunjukan musik kreatif yang unik. Pada 2004, ia mendirikan Komunitas Suling Bambu Nusantara (KSBN) sebagai wadah bagi siapa pun yang ingin merawat suling bambu.
KSBN kini berisi 24 anggota dengan beragam profesi dan usia: dua siswa SD, dua SMP, empat mahasiswa, satu guru TK, seorang pelukis, satu penyanyi, seorang penulis, dua freelance musik, dua ibu rumah tangga, dua driver ojol, tiga pegawai kantor, dan tiga orang pensiunan. Mereka bergabung karena ingin belajar, mencari ketenangan, atau sekadar penasaran dengan keunikan suling bambu dibanding recorder plastik atau flute. Bagi banyak anggota, suling bukan sekadar musik, tapi terapi yang menenangkan.
Suasana komunitas yang hangat terlihat dari kisah tiga anggota baru. Ibu Yuni (69), yang sebelumnya ikut komunitas angklung dan mengenal Pak Agus, tertarik bergabung untuk terapi vertigo sekaligus hiburan. Kanaya (14), siswi SMP kelas 3, awalnya diajak ibunya ikut KSBN. Saat pertama kali hadir, ia merasa komunitas ini hangat dan menerima semua orang, termasuk mereka yang belum bisa main suling, serta bangga bisa ikut melestarikan budaya suling bambu. Ibunya, Ibu Lis (48), melihat KSBN sebagai tempat membangun persaudaraan dan relasi, sekaligus sarana meditasi: meniup suling membuatnya merasa senang dan menenangkan.
Tak berhenti di komunitas, Agus juga mengembangkan karya kreatif lebih luas. Proyek seperti “The Sound of Pawon” konser dan pelatihan musik berbasis alat dapur mendapat hibah nasional.
Sejak 2010, ia membangun jaringan komunitas musik bambu di berbagai desa, menekankan kreativitas dan inklusivitas: suling, angklung, gamelan mini, semua bisa dijadikan medium berekspresi.
Meski begitu, perjalanan tidak selalu mudah. Latihan rutin di pendopo kadang harus terganggu karena dipakai untuk keperluan event lain, dan pendanaan komunitas ini masih bergantung pada iuran anggota. Namun Agus tetap konsisten, Ia percaya bahwa musik sederhana dari bambu masih punya ruang untuk menyentuh hati orang banyak.
Keistimewaan Agus bukan hanya terletak pada kemampuannya memainkan musik, tapi bagaimana ia menyalurkan filosofi itu ke komunitas.
Musik baginya adalah bahasa yang bisa menyatukan orang berbeda usia, latar, dan profesi. Dari napas bambu yang ia tiup, muncul rasa harmoni yang dirasakan seluruh anggota KSBN.
Di era ketika segala sesuatu berlomba untuk menjadi viral, Agus memilih konsistensi. Ia membuktikan bahwa eksistensi suatu hal seperti suling bambu bukan soal seberapa keras kita bersuara, melainkan seberapa lama gema itu bertahan. Suara suling bambu Pak Agus masih terdengar, menghubungkan manusia dengan musik, dan musik dengan kehidupan.