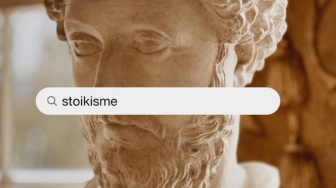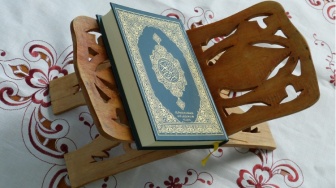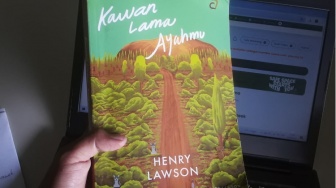Kabar penangkapan pria berinisial WFT (22) di Minahasa, yang diklaim sebagai salah satu pemilik akun Bjorka, menjadi berita besar. Namun, reaksi yang muncul di media sosial jauh lebih menarik daripada kronologi penangkapan.
Ada gelombang skeptisisme, bahkan sedikit kekecewaan. Lebih unik lagi, di antara warganet, Bjorka—sosok anonim yang notabene adalah penjahat siber yang memperjualbelikan data curian—justru mendapat pembelaan dan simpati.
Ini bukan kali pertama. Ketika Bjorka pertama kali muncul dengan klaim membocorkan data pejabat dan institusi vital negara pada 2022, banyak warganet yang justru bersorak. Slogan seperti "Bjorka Pahlawan" atau "Terima kasih, Bjorka" sempat ramai.
Fenomena ini menguak pertanyaan sosiologis, mengapa masyarakat cenderung merayakan hacker yang menyerang sistem negaranya sendiri?
Jawabannya terletak pada perasaan ketidakberdayaan kolektif dan bangkitnya Vigilante Digital.
Dalam psikologi sosial, vigilante adalah seseorang yang menjalankan hukum dan keadilan tanpa wewenang hukum yang sah. Di dunia siber Indonesia, Bjorka dianggap mengambil peran ini.
Memang, kebocoran data di Indonesia adalah kisah horor yang terus berulang. Mulai dari data BPJS, data pelanggan layanan seluler, hingga data e-commerce.
Pemerintah dan institusi seringkali merespons dengan pernyataan yang terkesan meremehkan, contohnya "data usang," "masih diselidiki," atau "tidak ada dampak signifikan". Respons yang dingin dan lamban ini yang menciptakan kekosongan kepercayaan.
Di tengah kekosongan itu, muncullah Bjorka.
Aksi Bjorka tidak hanya mencuri data, tetapi juga seringkali disertai dengan pesan-pesan politis dan sarkasme yang seolah menampar wajah institusi.
Inilah yang membuat narasi vigilante digital sangat kuat. Publik menilai kalau Bjorka bukanlah mencuri, melainkan membongkar. Ia adalah cermin yang memantulkan kelemahan sistem keamanan siber negara. Merayakan Bjorka adalah cara masyarakat sipil menyalurkan frustrasi terhadap kelalaian negara dalam mengurus hak privasi warga.
Aksi Bjorka, meski ilegal, menawarkan sesuatu yang tidak didapat publik dari saluran resmi, yaitu bukti nyata.
Ketika pemerintah mengatakan sistem aman, tapi Bjorka mengunggah tangkapan layar data yang bocor di forum gelap, publik lebih percaya pada bukti yang disajikan si peretas. Hal ini didukung oleh tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap birokrasi, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Penangkapan WFT di Minahasa, seorang pria muda yang mengaku belajar IT secara otodidak, justru menambah keruwetan narasi ini. Di satu sisi, polisi mengklaim menangkap pelaku kejahatan. Di sisi lain, muncul akun yang mengklaim "Aku masih bebas."
Kontradiksi ini semakin mengukuhkan skeptisisme masyarakat. Publik bertanya-tanya, apakah WFT adalah kambing hitam? Atau apakah Bjorka yang asli adalah jaringan yang jauh lebih besar?
Sobat Yoursay, penting untuk diingat bahwa terlepas dari narasi vigilante yang heroik, Bjorka tetap adalah pelaku kejahatan. Ia menjual data pribadi warga, yang bisa berujung pada kerugian finansial, penipuan, hingga doxing (penyebaran informasi pribadi secara ilegal).
Namun, respons simpatik publik harus kita baca sebagai kritik sosial yang pedas. Simpati kepada Bjorka adalah manifestasi dari kemarahan karena regulasi yang lamban, keamanan institusi yang lemah, hingga kesenjangan keadilan.
Jika negara ingin mengakhiri drama vigilante ini, fokusnya tidak boleh hanya pada penangkapan perorangan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada penangkapan Bjorka sebelumnya, menargetkan satu pelaku tidak akan membunuh Bjorka.
Satu-satunya cara untuk membungkam para vigilante digital dan mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan transparansi total mengenai kasus kebocoran data, penegakan hukum siber yang kuat terhadap institusi yang lalai, dan yang terpenting, investasi masif untuk memperkuat benteng digital nasional.
Sampai kelemahan fundamental ini teratasi, selama data kita masih bocor, dan selama respons institusi masih terkesan menutupi, maka narasi tentang "Pahlawan Bertopeng" di balik keyboard akan terus hidup, siap sedia untuk dirayakan kembali.
Sebab, dalam ketiadaan keadilan, manusia akan selalu mencari sosok yang bisa mewakili suara perlawanan mereka, bahkan jika sosok itu adalah seorang peretas.