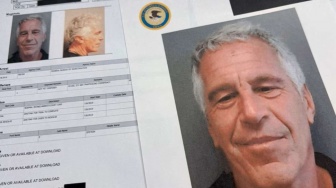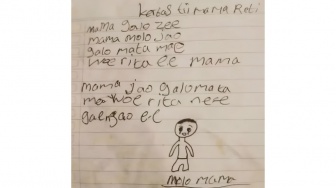Di kehidupan pesisir, hubungan manusia dengan alam tidak pernah bersifat abstrak. Alam bukan sekadar latar belakang kehidupan, melainkan penentu langsung nasib sehari-hari.
Ketika cuaca berubah, laut bergolak, atau musim meleset, dampaknya terasa seketika: hasil panen gagal, melaut ditunda, dan dapur rumah tangga terancam kosong. Tidak ada jarak antara sebab dan akibat. Alam berbicara, dan masyarakat pesisir langsung merasakannya di tubuh dan penghidupan mereka.
Di sinilah letak pelajaran penting yang sering luput dari pandangan masyarakat kota. Ketergantungan manusia pada alam di pesisir bersifat jujur dan tak bisa disangkal.
Berbeda dengan kota yang terlindung oleh teknologi, infrastruktur, dan sistem logistik, masyarakat pesisir menjadi kelompok pertama yang merasakan dampak krisis iklim, kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, hingga rusaknya ekosistem. Ironisnya, mereka bukan penyumbang utama kerusakan lingkungan tersebut.
Kota dapat menunda dampak, tetapi pesisir tidak memiliki kemewahan itu. Ketika hutan mangrove rusak, abrasi datang. Ketika laut tercemar, hasil tangkapan menurun.
Pesisir mengajarkan satu kebenaran yang sering kita hindari ketergantungan manusia pada alam bukan kelemahan, melainkan realitas. Yang menjadi masalah adalah ketika realitas ini hanya ditanggung oleh mereka yang berada di pinggiran, sementara pusat-pusat konsumsi tetap merasa aman dan jauh dari dampaknya.
Sekolah yang Terlepas dari Laut Pendidikan yang Tidak Ramah Konteks
Di tengah ketergantungan yang begitu kuat pada alam, muncul pertanyaan penting mengapa pendidikan di wilayah pesisir justru sering tidak berangkat dari realitas itu? Banyak anak pesisir duduk di bangku sekolah mempelajari konsep-konsep yang jauh dari kehidupan mereka sehari-hari, sementara pengetahuan lokal yang kaya justru terpinggirkan. Laut, angin, pasang surut, dan ekosistem pesisir jarang hadir sebagai sumber belajar yang sah.
Kurikulum nasional kerap datang dengan satu wajah yang sama, seolah-olah semua wilayah memiliki konteks hidup serupa. Padahal, kehidupan anak pesisir sarat dengan nilai ekologis, keterampilan bertahan hidup, dan pemahaman alam yang konkret. Ketika pengetahuan lokal tidak diakui sebagai bagian dari pendidikan formal, sekolah justru menciptakan jarak antara anak dan lingkungannya sendiri.
Ini bukan sekadar persoalan metode belajar, tetapi soal keadilan pengetahuan. Mengapa kearifan lokal pesisir jarang dianggap setara dengan pengetahuan resmi?
Padahal, pemahaman tentang laut, cuaca, dan ekosistem bukan hanya bernilai budaya, tetapi juga ekonomi dan ekologis. Ketika pendidikan gagal merangkul konteks, ia berpotensi melahirkan generasi yang tercerabut, tidak sepenuhnya diterima di dunia modern, namun juga terasing dari akar pesisirnya sendiri.
Belajar dari pesisir seharusnya berarti menjadikan alam sebagai ruang kelas terbuka, bukan sekadar latar geografis. Pendidikan yang ramah konteks bukan nostalgia, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis iklim yang kian nyata.
Bertahan Tanpa Kepastian Pesisir, Risiko, dan Makna Hidup Cukup
Hidup di pesisir berarti bekerja tanpa janji kepastian. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada jaminan cuaca, dan tidak ada kalender yang bisa memastikan hasil. Setiap hari adalah negosiasi dengan risiko. Namun, justru dari ketidakpastian inilah masyarakat pesisir mengajarkan satu pelajaran yang semakin langka keberanian hidup dengan kesadaran akan risiko.
Di tengah masyarakat modern yang terobsesi pada stabilitas dan prediktabilitas, pesisir menunjukkan bahwa hidup tidak selalu bisa diamankan sepenuhnya.
Ketahanan bukan dibangun dari jaminan, melainkan dari kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka belajar mengatur harapan, bekerja secukupnya, dan menerima bahwa tidak semua musim harus menghasilkan lebih.
Konsep cukup menjadi nilai penting di sini. Banyak masyarakat pesisir tidak mengejar akumulasi berlebih, melainkan keberlanjutan. Mereka memahami bahwa alam yang dieksploitasi berlebihan akan membalas dengan kehancuran. Pertanyaan kritis pun muncul, apakah ketamakan modern justru lahir dari keterputusan kita dengan alam?
Selain itu, pesisir juga menyimpan ingatan kolektif tentang kerja manual, tentang tangan, tubuh, dan waktu yang bergerak selaras. Di era mesin dan otomatisasi, kerja manual sering dianggap kuno dan tidak efisien. Namun, apakah modernisasi harus selalu menghapus jejak kerja manusia? Pesisir mengingatkan bahwa kerja bukan sekadar soal kecepatan, tetapi tentang relasi, ketekunan, dan kebermaknaan.
Belajar dari pesisir bukan sekadar belajar tentang laut atau mata pencaharian, tetapi tentang cara hidup yang sadar akan batas, risiko, dan keterhubungan.
Pesisir, yang sering dianggap pinggiran, justru menyimpan pelajaran paling mendasar tentang masa depan manusia bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari alam, dan bahwa keberlanjutan hanya mungkin jika ketergantungan itu diakui, bukan disangkal.