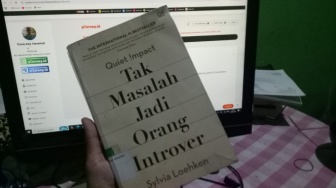Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya jadi kabar baik. Jutaan anak Indonesia akan mendapat jaminan makan siang bernutrisi setiap hari, sebuah upaya melawan stunting dan gizi buruk yang sudah lama menghantui negeri ini.
Tapi apa jadinya kalau program yang niatnya memberi gizi justru membawa anak-anak ke rumah sakit? Lebih ironis lagi, lembaga yang memimpin program ini ternyata nyaris tidak punya orang yang benar-benar paham soal gizi.
Data komposisi pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memang bikin alis terangkat. Dari sepuluh nama petinggi, tak satu pun punya latar belakang keilmuan gizi.
Ada Kepala BGN Dadan Hindayana, Brigjen Pol. Sony Sonjaya, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, Brigjen (Purn) Sarwono, Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman, dan beberapa nama lain yang sebagian besar berlatar belakang militer, kepolisian, atau birokrasi.
Rasa-rasanya seperti membaca daftar pejabat pertahanan, bukan lembaga yang seharusnya mengurusi kualitas makanan anak-anak.
Wajar jika publik mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah program bergizi bisa diawasi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi gizi?
Ini bukan sekadar urusan selera atau estetika makanan. Keselamatan pangan adalah ilmu yang jauh lebih kompleks, tentang kandungan nutrisi, proses penyimpanan, interaksi bahan, risiko kontaminasi, hingga standar higiene. Bukan hal yang bisa dikerjakan hanya dengan insting manajerial, apalagi pendekatan komando.
Masalah ini semakin terasa genting ketika melihat deretan kasus keracunan MBG dalam beberapa bulan terakhir.
Data Badan Gizi Nasional sendiri mencatat lebih dari 4.600 kasus keracunan sejak Januari hingga September 2025. Lembaga independen seperti CISDI bahkan melaporkan angka yang lebih tinggi, mencapai 7.119 kasus per 25 September.
Dari Banggai Kepulauan hingga Garut, dari Bandung Barat hingga Ketapang, ratusan anak masuk rumah sakit usai menyantap makanan yang seharusnya menyehatkan.
Di tengah kepanikan publik, pemerintah buru-buru merespons bahwa dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diperiksa, sertifikat laik higiene akan diwajibkan, dan SOP diperketat.
Tapi apakah semua itu cukup jika sejak awal lembaga pengawasnya tidak punya kapasitas ilmiah yang memadai? Bayangkan sebuah rumah sakit yang dikepalai jenderal, atau maskapai penerbangan yang direksi utamanya tak paham dunia aviasi. Bukan berarti mereka tak bisa belajar, tetapi risiko kesalahan kebijakan jelas membesar.
Fenomena militerisasi lembaga sipil memang bukan lagi hal yang aneh di negara kita.
Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga lembaga pangan, kehadiran purnawirawan TNI/Polri di pucuk pimpinan sudah seperti hal lumrah. Alasan yang kerap diajukan adalah soal kedisiplinan dan kemampuan manajerial.
Namun, ketika urusannya adalah gizi, alasan itu jadi terasa janggal. Apa relevansi pengalaman operasi militer dengan menentukan standar protein hewani atau kadar pestisida dalam sayur?
Kasus MBG seolah jadi ilustrasi nyata betapa pentingnya the right person in the right place.
Tanpa pemahaman mendalam soal rantai pasok pangan, pimpinan mungkin hanya fokus pada target angka, tentang berapa juta porsi sudah dibagikan dan berapa dapur dibuka, sementara detail teknis seperti suhu penyimpanan daging, risiko kontaminasi silang, atau kandungan gizi menu harian luput dari pengawasan.
Tak heran bila sertifikat laik higiene jadi solusi, meski hanya menambal di ujung rantai distribusi.
Di media sosial, kritik publik pun meluas. “Buset ini militer semua ini mah. Kacauuu,” tulis seorang pengguna Instagram. Yang lain menimpali, “Udah nggak kaget, apapun proyeknya ujungnya proyek bagi jabatan dan bagi hasil uang rakyat.”
Komentar-komentar ini adalah bentuk kegelisahan yang nyata, bahwa jabatan strategis lebih dilihat sebagai arena bagi-bagi kekuasaan ketimbang memastikan kompetensi teknis.
Padahal, di balik semua hiruk-pikuk politik, taruhannya adalah nyawa anak-anak. Setiap kali dapur MBG gagal menjaga standar kebersihan, risiko keracunan menghantui ribuan siswa.
Dan setiap kali kebijakan dibuat tanpa masukan ahli gizi, potensi kesalahan dalam penyusunan menu, takaran nutrisi, atau teknik penyimpanan semakin besar. Ini bukan sekadar soal satu atau dua pejabat, tetapi desain kelembagaan yang menempatkan popularitas dan loyalitas politik di atas keahlian.
Jika pucuk pimpinan tidak memahami risiko teknis, mereka bisa saja menyepelekan laporan lapangan atau menunda kebijakan penting hanya karena pertimbangan anggaran dan citra politik.
Program MBG sendiri sudah dikunci dalam APBN 2026 dengan anggaran fantastis Rp355 triliun. Dengan uang sebesar itu, publik berhak menuntut lebih dari sekadar jatah makan siang massal.
Kita berhak menuntut sistem pengawasan yang dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar tahu apa yang mereka awasi. Jika tidak, setiap piring nasi bergizi bisa berubah menjadi bom waktu, dan setiap anggaran besar hanya akan menambah daftar panjang proyek populis yang gagal melindungi rakyatnya.
Mungkin kini saatnya pemerintah berhenti berpura-pura bahwa manajemen bisa menggantikan kompetensi teknis.
Jika piring makan anak-anak diserahkan pada lembaga yang lebih paham barisan komando ketimbang kandungan protein, jangan heran bila hasilnya adalah gizi yang hilang dan kepercayaan publik yang ikut keracunan.