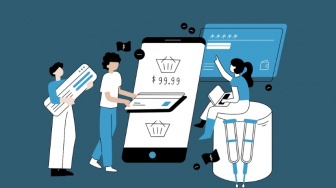“Jangan makan nasi itu, Bu. Itu bukan beras. Itu racun yang dibungkus janji.”
Banyu merebut piring plastik dari tangan Ibu yang gemetar. Di dalam piring itu, nasi putih mengepul hangat, hasil dari pembagian paket sembako raksasa yang dilakukan sore tadi di balai desa. Di luar, suara klakson truk-truk logistik bermerek “Relawan Bakti” masih meraung-raung, membagikan amplop dan kardus mi instan seolah-olah besok adalah hari kiamat.
“Tapi kita lapar, Banyu,” suara Ibu lirih. Matanya menatap nanar pada butiran nasi yang tumpah di lantai tanah. “Bapakmu butuh obat. Pak Bupati bilang ini sedekah tulus karena dia peduli pada orang kecil seperti kita.”
“Peduli?” Banyu tertawa getir.
“Dia peduli karena minggu depan adalah hari pencoblosan, Bu! Lihat ke jendela. Jembatan yang roboh tahun lalu masih jadi rongsokan. Puskesmas kita tidak punya tabung oksigen. Tapi lihat di lapangan desa, dia bisa membangun panggung konser megah dan membagikan ribuan ton beras dalam semalam. Itu bukan sedekah, Bu. Itu uang suap agar kita tetap diam saat mereka mencuri masa depan kita!”
Banyu adalah seorang pemuda putus sekolah yang bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bantuan-bantuan itu turun dari gudang-gudang rahasia milik perusahaan tambang yang izinnya baru saja diberikan oleh sang petahana.
Malam semakin larut, namun suasana desa semakin mencekam. Banyu memutuskan untuk keluar. Ia membawa sebuah kamera saku tua milik mendiang ayahnya. Ia memiliki firasat bahwa “pesta” sembako ini hanyalah kedok untuk sesuatu yang lebih besar.
Ia mengintai di balik semak-semak gudang distribusi pusat di ujung desa. Di sana, ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Puluhan truk bantuan tidak hanya berisi beras, tetapi juga ribuan lembar formulir C1 yang sudah terisi dan segel kotak suara yang tampak rusak. Di tengah kerumunan orang-orang bersafari, berdiri sang petahana, melipat tangan di dada sambil tertawa bersama kepala desa dan aparat setempat.
“Pastikan setiap warga yang menerima beras tadi sudah menandatangani surat pernyataan dukungan,” ujar sang petahana. Suaranya terdengar jelas di telinga Banyu melalui alat penyadap sederhana. “Jika ada yang membelot, ambil kembali bantuan itu, dan pastikan akses air ke sawah mereka terputus.”
Banyu gemetar. Ini bukan sekadar politik gentong babi, ini adalah penyanderaan massal. Ia segera mendekatkan kameranya, mengambil foto demi foto sebagai bukti autentik pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, sebuah bayangan panjang jatuh di atas tubuhnya.
“Kau punya mata yang terlalu tajam untuk seorang kuli, Banyu,” suara itu berat dan dingin.
Banyu berbalik dengan cepat, namun sebuah hantaman keras mendarat di pelipisnya. Ia tersungkur. Kamera sakunya dirampas oleh seorang pria bertubuh besar dengan seragam organisasi masyarakat setempat.
“Bawa dia ke dalam,” perintah sang petahana yang tiba-tiba sudah berdiri di depan Banyu.
Banyu diseret ke dalam gudang yang pengap. Ia diikat di sebuah kursi kayu, dikelilingi oleh tumpukan kardus mi instan yang bertumpuk hingga langit-langit—sebuah ironi di tengah perut yang melilit lapar.
“Kau tahu, Banyu,” sang petahana berjongkok di depan Banyu sambil memegang dagunya dengan kasar. “Rakyat itu seperti merpati. Kau beri jagung, mereka akan datang mematuk dari tanganmu. Kau tidak perlu membangun sekolah atau rumah sakit yang bagus karena itu membuat mereka pintar dan sulit diatur. Cukup beri mereka makan hari ini, maka mereka akan memberikan nyawanya untukmu besok.”
“Kau bajingan,” ludah Banyu mengenai sepatu kulit mengkilap pria itu.
Sang petahana tidak marah. Ia hanya tersenyum. “Malam ini, ibumu akan menerima paket spesial. Bukan beras, melainkan sebuah pesan: bahwa anak laki-lakinya sedang ‘belajar’ di kota dan tidak akan pulang untuk waktu yang sangat lama.”
Banyu berteriak histeris, mencoba melepaskan ikatan talinya. Namun, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar gudang. Bukan ledakan bom, melainkan suara ribuan orang yang berteriak secara serempak.
“Kembalikan air kami! Kembalikan tanah kami!”
Layar televisi besar di dalam gudang—yang tadinya menampilkan grafik kemenangan sang petahana—tiba-tiba berubah menjadi siaran langsung dari depan gudang itu sendiri. Ternyata, Banyu tidak sendirian. Ia telah menyalakan fitur auto-upload pada kameranya yang terhubung dengan akun media sosial milik komunitas pemuda desa yang ia kelola secara rahasia.
Foto-foto kecurangan yang baru saja ia ambil sudah tersebar luas. Warga desa yang tadinya diam karena takut, kini meledak amarahnya saat melihat foto sang petahana menginjak surat suara di dalam gudang.
“Sial! Cepat bubarkan mereka!” teriak sang petahana panik.
“Tidak bisa, Pak! Mereka memblokir jalan masuk!” lapor salah satu ajudannya dengan wajah pucat.
Massa yang marah mulai mendobrak pintu gudang. Di tengah kekacauan itu, Banyu melihat seseorang masuk dari pintu belakang. Bukan polisi, melainkan ibunya sendiri, membawa sebuah jeriken minyak tanah yang biasa digunakan untuk lampu di rumah mereka.
“Banyu!” teriak ibunya.
Ibunya tidak datang untuk memohon. Dengan mata yang menyala oleh keberanian yang belum pernah Banyu lihat sebelumnya, sang ibu menyiramkan minyak tanah ke tumpukan kardus sembako yang menjadi kebanggaan sang penguasa.
“Jika beras ini adalah rantai yang mengikat kami, maka biarkan api yang memutuskannya!” teriak ibunya sambil menyalakan pemantik.
Api menjilat tumpukan kardus dengan cepat. Ruangan itu segera dipenuhi asap hitam pekat. Sang petahana dan anak buahnya lari kocar-kacir menyelamatkan diri menuju pintu rahasia, meninggalkan Banyu yang masih terikat di kursi di tengah kobaran api.
Banyu batuk tersedak. Ia melihat ibunya mencoba membuka ikatan talinya, namun api sudah melingkupi mereka berdua. Atap gudang mulai runtuh, menjatuhkan balok-balok kayu yang membara.
“Pergi, Bu! Lari!” seru Banyu.
Ibunya menggeleng kuat. Ia berhasil memotong tali di tangan Banyu, namun tepat pada saat itu, sebuah tumpukan beras yang sangat berat roboh ke arah mereka, menutup jalan keluar tunggal. Di luar, suara massa semakin riuh bercampur dengan sirene pemadam kebakaran yang menderu dari jarak jauh. Namun, di dalam gudang, hening mulai berputar seiring dengan tipisnya oksigen.
Banyu memeluk ibunya erat-erat. Ia merasakan panas yang luar biasa, namun ia juga merasakan sesuatu yang aneh di balik dinding tempat mereka bersandar. Ada suara air mengalir deras. Banyu teringat sesuatu. Gudang ini dibangun tepat di atas instalasi pipa air utama tambang yang selama ini menyedot seluruh sumber air desa.
“Bu, pegangan yang kuat!” Banyu mengambil sebuah besi tajam, berjongkok, dan mulai menghancurkan pipa raksasa itu dengan sisa tenaganya.
BYAARRRR!
Air menyembur keluar dengan tekanan luar biasa, menghantam api dan merobohkan dinding gudang. Arus air yang sangat kuat menyeret Banyu dan ibunya keluar, terlempar ke tengah lapangan desa yang kini becek dan kacau.
Banyu terbatuk, menghirup udara yang penuh asap. Ia melihat warga desa berdiri membeku. Sang petahana sedang diseret oleh massa menuju kantor polisi, jas mewahnya kini compang-camping dan wajahnya penuh lumpur.
Banyu menarik napas dalam, merasakan udara malam yang dingin namun merdeka. Tetapi, saat ia merogoh sakunya, ia menyadari ponselnya masih menyala. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tersembunyi. Banyu mengangkatnya. Suara di seberang sana sangat tenang, suara seorang wanita yang terdengar sangat kuat.
“Kau pikir dengan membakar satu gudang permainan ini berakhir, Banyu? Kau baru saja menghancurkan investasi kami. Dan di dunia ini, utang harus dibayar dengan bunga yang sangat tinggi.”
Banyu tertegun, lalu menatap ibunya yang masih pingsan di pangkuannya. Ia melihat sebuah titik merah kecil dari laser sniper yang bergerak perlahan di dada ibunya.
Siapakah wanita di balik telepon itu? Apakah Banyu sanggup menyelamatkan ibunya di tengah sorak-sorai kemenangan warga yang semu? Dan apa yang sebenarnya tersimpan di bawah tanah desa itu selain sekadar air dan tambang?
Bantuan dari penguasa sering kali merupakan cara untuk menidurkan kesadaran rakyat. Kesejahteraan yang instan adalah musuh bagi kemajuan yang berkelanjutan. Dibutuhkan keberanian luar biasa untuk menolak “kenikmatan” yang ditawarkan demi mendapatkan martabat yang sejati, meski sering kali bayarannya adalah nyawa.